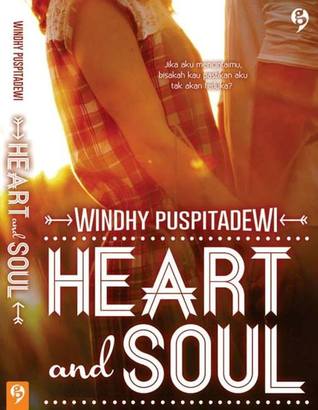CINTA YANG SALAH
Rafandha
“Ini adalah kue gemblong. Bukan kue getas.”
“Rendi, ini kue getas. Sepanjang yang kutahu,
dan sepanjang hidupku, nama kue itu tidak pernah berubah. GETAS.”
Aku melihat Rana menggembungkan pipinya lalu
meniup kue—yang masih kami perdebatkan namanya itu—di tangannya. Sudahkah kukatakan
bahwa ia tampak lucu dan menggemaskan ketika melakukan itu?
“Dulu, Ibu sering membuat ini saat aku masih
kecil. Ini dari tepung terigu, kan?”
Aku mengangguk lalu menyambar cepat kue yang
telah dingin itu dari tangannya. Ia menatapku dengan tatapan—apa—yang—sedang—kaulakukan
tapi kubalas dengan cengiran kuda.
Ia mengambil lagi kue yang ada di meja lalu
menjauhkan sedikit tempat duduknya dariku. “Tetapi, setahuku kue getas itu
dibalur gula pasir, bukan gula merah.”
Aku menoyor kepalanya cepat. “Sudah kubilang,
kan, ini adalah kue gemblong. Di Jakarta memang begini bentuknya,” ucapku.
“Tapi, apapun jenis gulanya, ini kue yang sama,
kok. Bentuknya sama, bahannya juga sama,” ujarnya tak memedulikan perkataanku, “sama
seperti cinta, bukan?” lanjutnya lalu mengerling ke arahku.
Aku terkesiap. Debaran di dadaku kembali datang
tanpa permisi.
“Cinta yang benar dan cinta yang salah
bagaimanapun ia tetap dalam wadah yang sama: cinta,” jelasnya lagi.
Aku mengambil teh hangat yang tersaji di meja
lalu menyesap dalam. Debaran itu masih saja terus ada. Kulihat matanya menerawang
ke langit-langit kota Jakarta yang samar karena kabut asap. Saat ini, kami
berdua duduk di pinggiran jalan—sesuatu yang sering kami lakukan sewaktu
kuliah. Dan tadi pagi, ia meneleponku untuk melakukan hal yang sama lagi.
“Tak ada namanya cinta yang benar dan cinta
yang salah,” sahutku. Ia lalu beralih menatapku. Kedua mata kami bertemu.
“Maksudmu?”
Aku mengangkat bahu lalu menaruh kembali
cangkir teh yang berada di tanganku ke meja. “Menurutku, yang ada hanya cara
mencintainya yang benar atau salah.”
Ia terdiam.
“Cinta itu tetaplah satu. Hanya saja terkadang
setiap individu yang melabelkannya ini itu. Padahal, tujuan dari cinta bukankah
harusnya membahagiakan?”
Ia kembali terdiam. Aku menghela napas. Deru
kendaraan mengisi kekosongan di antara kami berdua.
“Kemarin, aku melihat ia datang kembali. Hmm.
Anto?”
“Andre,” Rana menjawab cepat.
Aku tersenyum. “Ya, Andre. Saat itu kalian
berdua ada di kafe, kan? Aku kebetulan berada di sana. Dan kau tahu kejadian
selanjutnya,” ucapku.
Aku tak perlu menceritakan padanya terhadap apa
yang aku lihat kemarin. Bagaimana laki-laki itu berteriak mempermalukan wanita
itu di hadapan umum. Bagaimana tangan kasar laki-laki itu mendarat mulus di
pipi Rana. Dan bagaimana Rana menangis namun aku tak bisa berbuat apa-apa.
Tubuhnya bergetar. “Tapi aku mencintainya, Ren.
Cinta. Sangat cinta. Cinta yang salah, huh?” desahnya berat.
“Kau hanya merasa bahwa kau mencintainya, Rana.
Jika kau benar mencintainya, maka kau mencintainya dengan cara yang salah. Itu
bukan cinta. Membiarkannya menyakitimu—”
Aku geram. Tanganku mengepal. Ada sesak di
dalam dada yang sedari tadi melesak ingin keluar.
“Aku harus apa?” tanyanya lagi. Ada isakan yang
tertahan di sana.
“Lupakan ia. Cintai dengan cara yang benar. Kau
tahu, apapun namanya, mau gemblong atau getas, semuanya itu ada untuk
dinikmati,” ujarku lagi. Kali ini kuucapkan dengan nada serius agar ia
mengerti.
Kulihat ia menyeka air mata yang turun perlahan
dari sudut matanya.
“Berjanjilah, Rana. Berjanjilah padaku.
Berjanjilah pada sahabatmu—” aku menelan ludah, “sahabatmu ini.”
Ia menaikkan kepalanya dan sekali lagi kedua
mata kami bertemu. Dalam satu tarikan napas, ia berujar mantap, “Aku berjanji!”
Aku terkekeh geli melihat air mukanya. Masih
saja menggemaskan.
“Sekarang, lupakan itu. Mari kembali makan!”
sahutnya antusias lalu kembali mengambil kue itu.
Aku pun ikut-ikutan.
“Eh, Ren. Bagaimana cara mencintai yang benar?”
tanyanya lagi sambil beralih menatapku.
Aku menghela napas lalu mengembuskannya. “Seperti
caraku mencintaimu.”
*
Diikutkan dalam tantangan #RabuMenulis Gagasmedia.